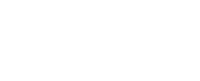- CETAK KARTU PVC
CETAK KARTU PVC
- CETAK KARTU NAMA
- CETAK KARTU RFID
CETAK KARTU RFID
- CETAK TALI ID CARD / LANYARD
CETAK TALI ID CARD/ LANYARD
- TALI GELANG LANYARD
TALI GELANG LANYARD
- CETAK FLASHDISK CARD
CETAK FLASHDISK CARD
- AKSESORIS ID CARD
AKSESORIS ID CARD
- FINISHING KARTU
FINISHING KARTU
Orang Asia di Jerman Jadi Target Stereotip Rasisme dan KekerasanOrang Asia di Jerman Jadi Target Stereotip Rasisme dan Kekerasan
“Oi Cina, Asia, kenapa kamu di sini?” Kata-kata ini ditujukan kepada Zacky, seorang pelajar asal Indonesia di Jerman, saat dia berjalan di Berlin. Lain waktu, dia benar-benar dipukul oleh seorang laki-laki saat berjalan di dekat Museum Sejarah Alam di kota itu.
Sementara Puspa, orang Indonesia yang tengah belajar di Universitas Bonn, berbagi pengalamannya saat diperlakukan secara rasis. Dia sedang dalam perjalanan pulang dari rumah seorang teman pada malam tahun baru ketika “seseorang melemparkan kembang api ke arah saya,” cerita Puspa. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, dia “cukup yakin” lemparan itu terjadi karena dia mengenakan jilbab.
Pembuat film dokumenter asal Cina yang tinggal di Berlin, Popo Fan, menceritakan pengalaman mengerikan tentang rasisme di kereta bawah tanah di Berlin. Pada tahun 2019 sebelum pandemi, Fan tengah berada di stasiun Kottbusser Tor dan seseorang menyuruhnya “pulang ke Cina”.
Saat insiden terjadi, ada tujuh atau delapan orang lain di tempat yang sama. “Tidak ada yang membantu saya sama sekali, bahkan tidak ada yang menengok,” katanya. “Mereka melihat ke ponsel atau memalingkan muka.”
Rasisme berakar di masyarakat Jerman
Sikap rasis terhadap orang-orang yang berasal dari Asia telah menjadi perhatian setelah merebaknya pandemi Covid-19 dan dugaan asalnya di kota Wuhan di Cina. Namun prasangka rasial terhadap orang Asia telah lama didapati di Jerman.
Di bawah rezim Nazi, orang Cina yang tinggal di Jerman diusir atau dideportasi ke kamp konsentrasi dan kamp kerja paksa. Tetapi rasisme anti-Asia yang paling meluas terjadi pada dekade setelah penyatuan kembali Jerman.
Sasarannya sebagian besar adalah para migran dari Vietnam yang awalnya datang ke Jerman Timur sebagai bagian dari program mendatangkan pekerja dari rezim komunis lainnya. Hampir 60.000 pekerja kontrak dari Vietnam tinggal di Jerman Timur ketika Tembok Berlin runtuh pada tahun 1989.
Dua tahun kemudian, neo-Nazi menyerang para pedagang asal Vietnam di Hoyerswerda di negara bagian Sachsen. Mereka juga membentuk gerombolan di luar tempat penampungan para migran dan melakukan pelecehan terhadap warga penampungan.
Kerusuhan antiimigran yang lebih parah pernah terjadi di Rostock-Lichtenhagen tahun 1992 ketika sekitar 2.000 ekstremis sayap kanan menyerang dan mengebom blok perumahan yang dipenuhi oleh pekerja kontrak asal Vietnam. Ribuan orang dilaporkan memuji tindakan para ekstremis tersebut, sementara polisi tidak berbuat banyak untuk menghentikan serangan itu.
“Gambar ini telah membentuk banyak orang yang kini berjuang melawan rasisme di Jerman,” kata Ferat Ali Kocak, seorang aktivis antirasisme di Berlin. “Jelas bagi kami bahwa karena berbagai alasan, rasisme anti-Asia, meskipun tidak selalu terlihat, tertanam kuat dalam masyarakat Jerman.”
Meningkatnya rasisme anti-Asia sejak pandemi
Sejak wabah Covid-19 di Jerman tahun lalu, prasangka ini semakin terlihat. Pembuat film Popo Fan ingat pernah diteriaki dan dikatai “corona” di kereta bawah tanah.
“Saya melapor ke polisi dan mengatakan bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Mereka tidak melakukan apa-apa. Saya bertanya kepada mereka, tunggu apa lagi? Tunggu saya ditembak pakai senjata?” kenangnya. Fan sejak itu memutuskan untuk menjaga jarak dengan sistem transportasi umum di Berlin.
Pengalaman tersebut meninggalkan kenangan traumatis.
“Anda tidak mengidap Covid, ‘kan?” seorang teman bertanya kepada Michelle, seorang profesional muda asal Cina yang tinggal di Bonn. Meskipun komentar tersebut dapat diartikan sebagai rasisme, Michelle mengatakan dia mengerti mengapa orang berperilaku seperti ini.
“Itu manusiawi dan ada hubungannya dengan Cina karena virus itu mungkin berasal dari sana,” katanya kepada DW. Dia menggambarkan di Cina sendiri juga ada diskriminasi terkait dengan virus itu. Orang-orang dari provinsi Hubei, tempat kasus Covid pertama terjadi, mendapat stigma sosial dan dikurung di rumah-rumah.
Stereotip diawetkan dalam budaya populer
Rasisme anti-Asia di Jerman datang dalam berbagai banyak bentuk, kata Popo Fan, yang mencatat bahwa televisi Jerman hampir tidak pernah menampilkan karakter Asia. Bahkan ketika ada orang Asia muncul di layar, mereka cenderung menggambarkan stereotip seperti pelayan di restoran Asia, atau seorang perempuan muda yang bekerja di spa, katanya.
Prasangka juga bisa ditemui di dunia kencan. “Di komunitas queer juga ada stereotipnya,” ungkap Fan. “Para lelaki di Grindr (aplikasi kencan untuk lelaki gay, biseksual, transseksual, komunitas queer, red.) mengatakan bahwa mereka tidak akan berhubungan dengan pria Asia karena dengar-dengar itu seperti berhubungan seks dengan lumba-lumba. Sungguh hal yang mengerikan untuk diucapkan.”
Contoh lain rasisme anti-Asia di media Jerman yang baru-baru ini menjadi berita utama adalah ketika Matthias Matuschik, seorang presenter di stasiun radio Bayern 3, membandingkan boy band K-pop BTS dengan COVID-19 setelah mereka menyanyikan lagu Coldplay yang berjudul Fix You. Matuschik menggambarkan BTS sebagai “virus jelek yang mudah-mudahan akan segera ada vaksinnya juga.”
Reaksi yang timbul media sosial kemudian ibarat bola liar.
Namun Michelle, perempuan muda asal Cina yang tinggal di Bonn, mengatakan bahwa dia merasa diterima di Jerman. “Orang yang membutuhkan petunjuk arah sering mendatangi saya dan meminta bantuan meskipun saya terlihat seperti orang asing,” katanya. Awalnya, dia merasakan ada diskriminasi, tetapi dia yakin itu terkait dengan kesalahpahaman budaya.
Promosikan dialog antarbudaya untuk generasi muda
Di lain pihak, para pemuda Jerman kini lebih banyak terlibat dengan isu-isu seperti rasisme dan seringkali lebih terbuka dan menerima. Demikian menurut Frank Joung, pembawa acara podcast Halbe Kattofl yang mempromosikan dialog antara orang Jerman berlatar belakang imigran.
“Mereka [anak muda] mengobrol dengan orang-orang di seluruh dunia, mereka terhubung melalui aplikasi, mereka mendengarkan K-pop, menonton Black Panther. Saya pikir bagi mereka, ini cara yang logis – mereka bahkan tidak memikirkan siapa yang ‘berkulit hitam’ ‘atau’ putih’,” kata Joung.
Aktivis antirasisme Ferat Ali Kocak berbagi sentimen ini. “Dengan adanya gerakan Black Lives Matter dan gerakan antirasisme setelah Hanau, sesuatu telah terjadi,” katanya, merujuk pada penembakan massal Februari 2020 di sebuah bar shisha yang menewaskan beberapa orang keturunan Turki di kota dekat Frankfurt.
“Kita hidup di dunia yang tidak adil di sini dan kita butuh lebih banyak solidaritas,” tambah Kocak. “Orang-orang muda menyadari hak ini dan turun ke jalan.”